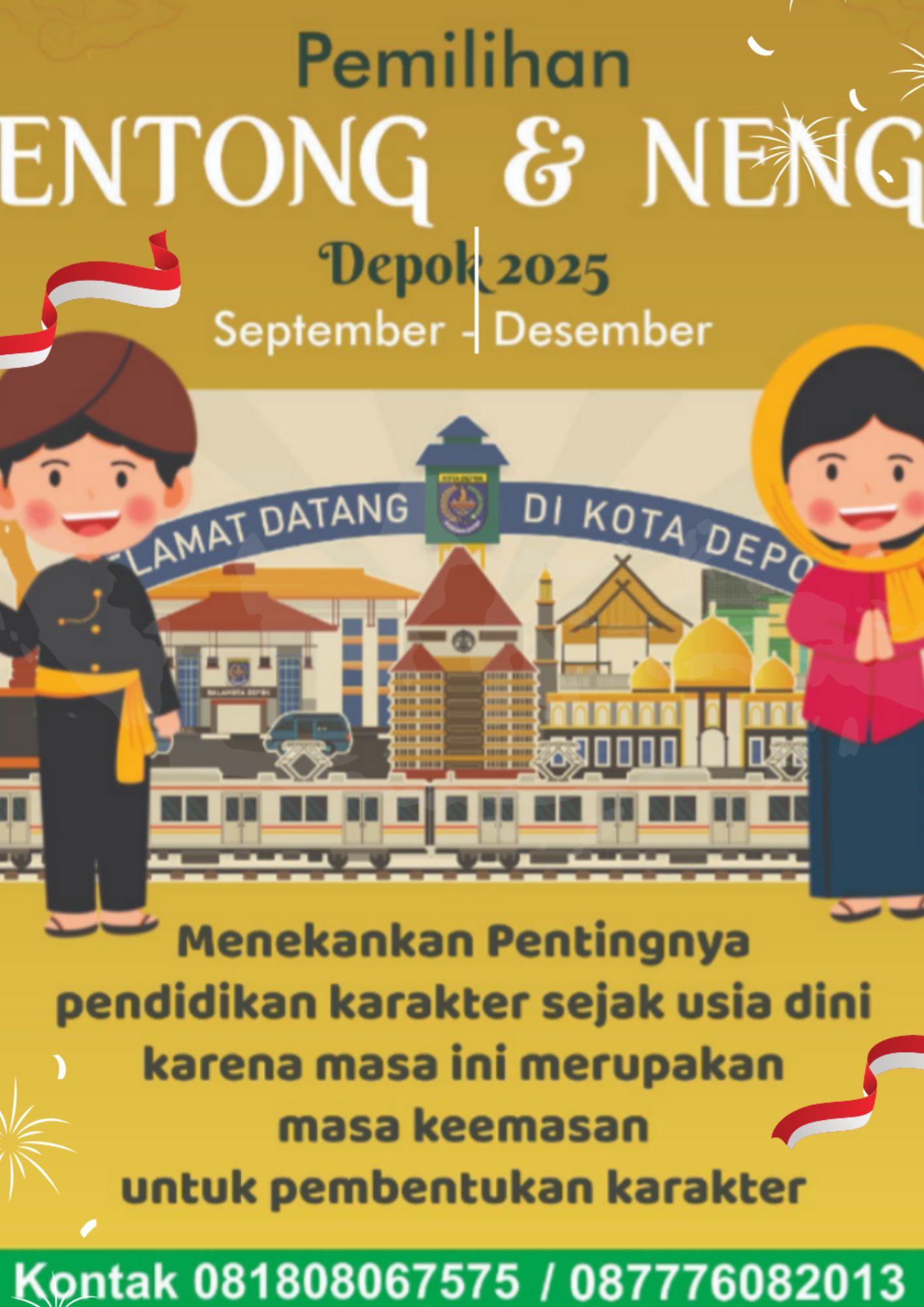www.mediapresisihukum.com | OPINI PUBLIK Oleh Rahmat Ardiansyah | Mahasiswa Universitas Pamulang Tangerang Selatan
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Bayangkan sebuah dunia di mana suara seseorang hanya terdengar jika ada kamera yang menyorotnya. Sebuah kasus kekerasan, penipuan, atau ketidakadilan lainnya bisa saja tenggelam tanpa jejak kecuali jika ada yang mengunggahnya ke media sosial.
Fenomena inilah yang dikenal dengan istilah “No Viral No Justice.” Sebuah ironi dalam penegakan hukum, di mana keadilan seolah harus diperjuangkan bukan di ruang sidang, melainkan di kolom komentar dan trending topic.
Istilah ini merujuk pada kecenderungan aparat penegak hukum yang baru bertindak setelah kasus tertentu viral di media sosial. Sebelum viral? Laporan masyarakat sering diabaikan, dijawab dengan prosedur berbelit, atau lebih buruk tidak direspons sama sekali.
Fenomena “No Viral No Justice” mencerminkan tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia.
Istilah ini menggambarkan situasi di mana aparat penegak hukum baru bertindak setelah kasus tertentu menjadi viral di media sosial. Sebelum viral, banyak laporan masyarakat yang diabaikan atau tidak ditindaklanjuti dengan serius.(Sumber KOMPAS.com).
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai bahwa fenomena ini mencerminkan penegakan hukum di Indonesia yang belum berjalan baik. Ia menyoroti bahwa banyak kasus yang baru mendapatkan perhatian setelah viral di media sosial, seperti kasus penggusuran rumah warga di Pulau Rempang, Batam, yang menjadi sorotan setelah viral di media sosial.(Sumber Kompas).
Fenomena ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia belum mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara menyeluruh. Bivitri menekankan bahwa kejadian hukum di Indonesia sebaiknya dilihat dari perspektif sistemik, bukan individu. Ia juga menyoroti pentingnya reformasi hukum oleh pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus seperti extrajudicial killing, korupsi, dan masalah hukum lainnya.(Sumber Kompas)
Fenomena “No Viral No Justice” memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap sistem hukum dan masyarakat. Pertama, fenomena ini menciptakan kesenjangan dalam memberikan keadilan, terutama bagi korban yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat advokasi. Kedua, fenomena ini mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum formal. Masyarakat merasa bahwa penegakan hukum sering kali tidak responsif terhadap kasus-kasus tertentu kecuali jika mendapatkan perhatian luas masyarakat (ResearchGate)
Ketiga, fenomena ini dapat mencoreng nama baik institusi penegak hukum, seperti Polri, dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Rudianto, seorang pengamat, menyatakan bahwa perilaku oknum-oknum yang mengabaikan laporan-laporan polisi dapat mencoreng nama baik Polri dan menggerus kepercayaan publik pada Korps Bhayangkara. (Sumber metronews)
Sepanjang tahun 2024, terdapat beberapa kasus yang baru ditangani setelah viral di media sosial. Berikut di antaranya:(Sukabumi update)
1. Kasus Perundungan di SMA Binus: Pada 19 Februari 2024, nama artis VR menjadi sorotan setelah anaknya, LR (17 tahun), terlibat kasus perundungan bersama teman-temannya di SMA Binus International Serpong. Peristiwa ini ramai dibicarakan di media sosial, terutama di platform X , di mana banyak pengguna menyuarakan kecaman terhadap insiden tersebut. Para netizen beramai-ramai mendesak agar kasus ini segera diusut oleh pihak berwenang, dengan komentar seperti “Coba bantu viralkan, gaes! No viral, no justice,” yang ramai diunggah oleh pengguna .(Sukabumi update)
2. Kasus Vina Cirebon : Kasus pembunuhan seorang anak berusia 13 tahun berinisial AM sempat menjadi sorotan oleh pengguna media sosial di Indonesia. Afif ditemukan tewas di Sungai Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, pada 9 Juni 2023. Kasus ini baru mendapatkan perhatian setelah viral di media sosial, yang kemudian mendorong pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Fenomena “No Viral No Justice” menyoroti perlunya reformasi dalam sistem hukum Indonesia.
Sistem hukum harus mampu merespons laporan masyarakat dengan cepat dan adil, tanpa harus menunggu tekanan dari media sosial. Hal ini membutuhkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam penegakan hukum.(Sumber Kompas)
Selain itu, penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Masyarakat harus merasa bahwa mereka dapat mengandalkan sistem hukum untuk mendapatkan keadilan, tanpa harus mengandalkan viralitas di media sosial. Ini dapat dicapai melalui edukasi hukum, peningkatan akses terhadap bantuan hukum, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses penegakan hukum.
Akhirnya, fenomena “No Viral No Justice” mengingatkan kita bahwa keadilan sejati tidak seharusnya bergantung pada seberapa banyak like dan share yang didapatkan di media sosial. Keadilan harus menjadi hak setiap individu, terlepas dari kemampuan mereka untuk membuat kasus mereka viral. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum yang komprehensif dan inklusif menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi.
Bayangkan sebuah dunia di mana suara seseorang hanya terdengar jika ada kamera yang menyorotnya. Sebuah kasus kekerasan, penipuan, atau ketidakadilan lainnya bisa saja tenggelam tanpa jejak kecuali jika ada yang mengunggahnya ke media sosial. Fenomena inilah yang dikenal dengan istilah “No Viral No Justice.” Sebuah ironi dalam penegakan hukum, di mana keadilan seolah harus diperjuangkan bukan di ruang sidang, melainkan di kolom komentar dan trending topic.
Istilah ini merujuk pada kecenderungan aparat penegak hukum yang baru bertindak setelah kasus tertentu viral di media sosial. Sebelum viral?
Laporan masyarakat sering diabaikan, dijawab dengan prosedur berbelit, atau lebih buruk tidak direspons sama sekali.
Media sosial telah berubah dari sekadar tempat berbagi menjadi ruang kontrol sosial. Netizen menjadi jaksa, hakim, dan juga juru kampanye. Mereka bisa menyuarakan ketidakadilan lebih cepat dari media arus utama. Aparat hukum pun tidak bisa menutup mata karena viralitas menciptakan tekanan publik yang sulit diabaikan.
Fenomena ini tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari luka-luka lama masyarakat terhadap sistem hukum. Laporan yang tak ditanggapi. Kasus yang jalan di tempat. Proses hukum yang lamban, bias, atau bahkan sarat konflik kepentingan. Maka muncullah kebutuhan untuk menggugah dunia dan dunia kini berarti media sosial.
Keadilan, dalam konteks ini, bukan lagi tentang benar atau salah di mata hukum, tapi tentang siapa yang paling banyak mendapat perhatian.
Salah satu contoh nyata adalah kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang karyawati toko roti di Jakarta Timur. Meskipun korban telah melaporkan kejadian tersebut pada Oktober 2024, respons dari aparat penegak hukum baru muncul setelah video penganiayaan itu viral di media sosial pada Desember 2024. Kasus ini menyoroti bagaimana perhatian serius dari aparat hukum sering kali baru muncul seiring dengan viralnya sebuah kasus di media sosial .(Antara News)
Fenomena “No Viral No Justice” mencerminkan keresahan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Istilah ini menggambarkan situasi di mana keadilan bagi korban atau pihak yang dirugikan baru dapat tercapai setelah kasusnya viral di media sosial.
Media sosial kini menjadi alat yang semakin krusial bagi warganet dalam berpartisipasi aktif dalam mewujudkan keadilan dan meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. Dengan berbagai platform media sosial, warganet dapat dengan cepat menyebarkan informasi, memobilisasi dukungan publik, dan mengawasi tindakan penegak hukum. Namun, ketergantungan pada viralitas sebagai katalisator penegakan hukum berpotensi menimbulkan ketidakmerataan perhatian terhadap kasus-kasus tertentu, sehingga menuntut reformasi yang mendalam dalam sistem hukum nasional. (Sumber Antara News)
Fenomena “No Viral No Justice” seharusnya menjadi cermin bagi kita semua bahwa sistem hukum kita perlu berbenah. Keadilan tidak boleh bergantung pada seberapa viral sebuah kasus di media sosial. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, transparan, dan adil tanpa memandang status sosial atau tekanan publik.(Antara News)
Peningkatan akuntabilitas dan responsivitas terhadap laporan masyarakat dapat membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Dengan demikian, kita dapat membangun sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan tidak bergantung pada viralitas semata. (Sumber Antara News)
Di era digital ini, media sosial telah menjadi alat yang ampuh dalam menyuarakan ketidakadilan. Namun, fenomena “No Viral No Justice” mencerminkan kenyataan pahit bahwa keadilan sering kali baru ditegakkan setelah kasus tertentu viral di dunia maya.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat bahwa banyak laporan masyarakat yang tidak diproses dengan baik oleh kepolisian. Belly Stanio, pengacara publik LBH Jakarta, mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang merasa bingung dan frustrasi ketika laporan mereka tidak ditindaklanjuti. Akibatnya, mereka memilih untuk memviralkan kasus mereka di media sosial agar mendapat perhatian dan keadilan.
(Sumber Metronews)
Studi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) juga menunjukkan adanya korelasi kuat antara pemberitaan media dan percepatan penanganan kasus. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak selalu bekerja atas dasar prinsip keadilan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan dari opini publik.
Fenomena ini mencerminkan ketimpangan dalam respons hukum, di mana kasus-kasus yang tidak mendapat sorotan media sering kali terabaikan. Ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah keadilan hanya milik mereka yang mampu membuat kasusnya viral?
Ketergantungan pada viralitas untuk mendapatkan keadilan tidak hanya mencerminkan kelemahan sistem hukum, tetapi juga berdampak pada masyarakat.
Korban kejahatan yang tidak mampu membuat kasusnya viral merasa diabaikan dan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum.
Selain itu, tekanan untuk membuat kasus viral dapat menimbulkan stres tambahan bagi korban. Mereka harus menghadapi sorotan publik, komentar negatif, dan bahkan ancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Fenomena ini juga menciptakan ketidakadilan baru, di mana mereka yang memiliki akses ke media sosial dan jaringan yang luas lebih mungkin mendapatkan keadilan dibandingkan mereka yang tidak.
Fenomena “No Viral No Justice” seharusnya menjadi cermin bagi kita semua bahwa sistem hukum kita perlu berbenah. Keadilan tidak boleh bergantung pada seberapa viral sebuah kasus di media sosial. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, transparan, dan adil tanpa memandang status sosial atau tekanan publik.
Peningkatan akuntabilitas dan responsivitas terhadap laporan masyarakat dapat membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dengan demikian, kita dapat membangun sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan tidak bergantung pada viralitas semata.
Dalam era digital yang serba cepat ini, media sosial telah menjadi alat yang ampuh dalam menyuarakan ketidakadilan. Namun, fenomena “No Viral No Justice” mencerminkan kenyataan pahit bahwa keadilan sering kali baru ditegakkan setelah kasus tertentu viral di dunia maya.
BN, seorang guru honorer di SMAN 7 Mataram, menjadi korban pelecehan seksual oleh kepala sekolahnya. Untuk melindungi diri, ia merekam percakapan telepon yang berisi ujaran tidak senonoh dari atasannya. Ironisnya, alih-alih mendapatkan perlindungan, BN justru dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan divonis bersalah oleh Mahkamah Agung.(Sumber BBC)
Kasus ini baru mendapat perhatian luas setelah viral di media sosial dan munculnya petisi daring yang mendukung BN. Dukungan publik yang masif akhirnya mendorong Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada BN, membebaskannya dari hukuman penjara dan denda. FS, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir NYH. Awalnya, kasus ini ingin ditutup rapat dengan skenario baku tembak yang direkayasa. Namun, berkat sorotan media dan viralitas di publik, fakta-fakta sebenarnya mulai terungkap.(Sumber kontan co id)
Tekanan publik yang masif memaksa Polri untuk membentuk tim khusus guna mengusut tuntas kasus ini. Akhirnya, FS dan beberapa orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman berat. Kasus ini menjadi pukulan telak bagi citra Polri dan menunjukkan betapa pentingnya peran publik dalam mengawal keadilan.
MDY, anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak, melakukan penganiayaan brutal terhadap seorang remaja bernama DO.
Video penganiayaan tersebut tersebar luas di media sosial, memicu kemarahan publik.(Instagram)
Viralitas video tersebut mendorong penegak hukum untuk bertindak cepat. MD ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Kasus ini juga membuka tabir gaya hidup mewah dan arogansi anak pejabat yang selama ini tersembunyi.
Ketiga kasus di atas menunjukkan bahwa tanpa viralitas di media sosial, keadilan mungkin tidak akan terwujud. Fenomena “No Viral No Justice” mencerminkan kelemahan sistem hukum kita yang masih bergantung pada tekanan publik untuk bertindak.
Sebagai masyarakat, kita perlu terus mengawal dan mendorong reformasi sistem hukum agar keadilan tidak lagi bergantung pada seberapa viral sebuah kasus di media sosial. Keadilan harus ditegakkan berdasarkan prinsip hukum yang adil dan transparan, bukan karena tekanan publik semata.
Di era digital yang serba cepat ini, media sosial telah menjadi alat yang ampuh dalam menyuarakan ketidakadilan. Namun, fenomena “No Viral No Justice” mencerminkan kenyataan pahit bahwa keadilan sering kali baru ditegakkan setelah kasus tertentu viral di dunia maya.
Ketika sebuah kasus menjadi viral, publik seringkali sudah menghakimi sebelum pengadilan memutuskan.
Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dilanggar oleh netizen. Orang yang dituduh langsung dilabeli bersalah. Ini membahayakan sistem hukum yang seharusnya berdasarkan bukti, bukan asumsi.(Journal Universitas Pasundan)
Fenomena ini dikenal sebagai “trial by media” atau “trial by social media,” di mana opini publik yang terbentuk melalui media sosial dapat mempengaruhi proses hukum dan persepsi terhadap tersangka.(Sumber Segaris co)
Trial by media dapat memiliki dampak serius terhadap sistem hukum, antara lain:
• Pengaruh terhadap Aparat Penegak Hukum : Tekanan publik yang masif di media sosial bisa memengaruhi netralitas penyidikan, penuntutan, bahkan putusan pengadilan karena adanya tekanan untuk “memuaskan” keinginan publik, bukan berdasarkan bukti dan hukum. (Sumber Segaris co)
• Kerusakan Reputasi dan Dampak Psikologis: Riuh konten yang tersebar di dunia maya menciptakan opini publik yang dapat menyudutkan orang yang masih dalam tahap penyidikan. Sayangnya, meskipun nantinya terbukti tidak bersalah, kerusakan reputasi dan dampak psikologis yang mereka alami akan kekal dalam naungan internet. (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)
• Pelanggaran Asas Praduga Tak Bersalah : Trial by the press yang mengakibatkan trial by the public dapat mempengaruhi aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana karena tergiring oleh opini publik. Aparat penegak hukum takut melawan opini publik karena takut dihujat oleh masyarakat. (Journal Universitas Pasundan)
Untuk menghindari dampak negatif trial by media, beberapa langkah dapat diambil :
• Penerapan Kode Etik Jurnalistik: Pers harus menjaga prinsip-prinsip jurnalistik, termasuk asas praduga tak bersalah, dalam pemberitaan mereka.(Open Journal Systems)
• Peningkatan Literasi Media: Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi.(Sumber Segaris co)
• Transparansi Proses Hukum : Aparat penegak hukum harus menjaga transparansi dalam proses hukum untuk membangun kepercayaan publik tanpa harus menunggu viralitas kasus.
Di era digital saat ini, fenomena “No Viral No Justice” mencerminkan realitas pahit dalam penegakan hukum di Indonesia. Keadilan sering kali baru ditegakkan setelah kasus tertentu viral di media sosial. Namun, tidak semua orang memiliki akses atau kemampuan untuk membuat kasus mereka viral. Mereka yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat adat, atau kalangan miskin tanpa akses digital sering kali tidak mendapat perhatian. Akibatnya, keadilan tidak lagi universal, melainkan menjadi privilege bagi mereka yang memiliki koneksi dan kemampuan digital.
Fenomena ini menciptakan kasta baru dalam hukum: mereka yang mampu mengakses media untuk diviralkan, dan mereka yang tidak. Korban di pedalaman, masyarakat adat, atau kalangan miskin tanpa akses digital, seringkali tidak mendapat perhatian. Maka, keadilan tidak lagi universal.
Menurut Bivitri Susanti, pengamat hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, fenomena “No Viral No Justice” terjadi karena sistem hukum belum memberikan ruang yang cukup bagi warga negara biasa untuk mengadu dan memastikan pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan baik .(Sumber KOMPAS com)
Ketimpangan ini berdampak pada :
• Kehilangan Kepercayaan terhadap Sistem Hukum: Masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan karena kasus mereka tidak viral cenderung kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum.
• Meningkatnya Ketidakadilan Sosial: Ketimpangan ini memperparah ketidakadilan sosial yang sudah ada, karena hanya mereka yang memiliki akses digital yang dapat memperjuangkan keadilan.
• Pelanggaran terhadap Prinsip Equality Before the Law : Fenomena ini bertentangan dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum, di mana setiap orang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang status sosial atau kemampuan teknologi.
Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan :
• Peningkatan Akses terhadap Teknologi : Memberikan akses teknologi kepada masyarakat di daerah terpencil agar mereka dapat menyuarakan kasus mereka.
• Penguatan Lembaga Bantuan Hukum : Memperkuat lembaga bantuan hukum agar dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki akses digital dalam memperjuangkan keadilan.
• Reformasi Sistem Hukum : Melakukan reformasi sistem hukum agar lebih responsif terhadap laporan masyarakat tanpa harus menunggu viralitas kasus.(Sumber Antara News)
Bayangkan seorang perempuan muda, sebut saja namanya A. Ia datang dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Sehari-harinya ia bekerja di sebuah toko kelontong dan pulang malam. Suatu hari, hidupnya berubah drastis ketika ia menjadi korban pelecehan seksual oleh atasannya sendiri. Tapi yang lebih menghancurkan dari kejadian itu adalah ketika ia akhirnya memberanikan diri untuk bersuara.
Tidak ada keadilan yang datang secara otomatis. Laporan ke polisi tidak membuahkan hasil. Bukti dianggap kurang. Dan pelaku? Masih bebas berkeliaran, masih bekerja di toko yang sama, masih bisa tertawa di atas trauma yang ia ciptakan.
Hingga akhirnya, seorang aktivis lokal membantu A menuliskan kisahnya di media sosial. Dalam hitungan jam, ribuan orang membacanya. Dalam hitungan hari, media mengangkat kisahnya. Dalam hitungan minggu, tekanan publik begitu besar hingga aparat akhirnya bergerak. A akhirnya mendapatkan keadilan yang ia perjuangkan.
Namun, keadilan itu datang dengan harga.
Ketika kisah A viral, yang tersebar bukan hanya kebenaran, tapi juga fragmen-fragmen pribadinya. Wajahnya mulai dikenal. Lingkungannya bergosip. Teman-teman menjauh. Bahkan keluarganya ikut mendapat tekanan. Bukannya perlindungan, ia justru seperti menjadi sasaran baru oleh mereka yang meragukan ceritanya, memojokkannya, atau bahkan membelanya berlebihan hingga ia merasa lebih seperti simbol daripada manusia.
Ia tidak hanya menjadi korban dari satu orang pelaku, tapi juga dari ekspektasi publik yang begitu besar. Setiap geraknya di media sosial diperhatikan. Bahkan sekadar mengunggah foto tersenyum dianggap kontroversial.
“Kalau kamu benar-benar trauma, kok masih bisa selfie?” tulis seorang netizen.
Helmi Yahya pernah berkata, “Di era digital, informasi menyebar lebih cepat dari empati.” Dan Anisa merasakannya langsung.
Kasus A bukan satu-satunya. Kita bisa melihat beragam kisah viral yang, alih-alih murni membela korban, justru memperjualbelikan cerita mereka untuk like, retweet, dan views. Tidak sedikit aktivis instan—atau mereka yang mengklaim sebagai pembela korban yang menyebarkan kisah dengan penuh semangat tapi tanpa izin dari korban sendiri.
Mereka merekam korban menangis. Mereka mempublikasikan surat laporan polisi. Mereka membuka identitas korban dengan dalih agar dunia tahu, agar keadilan ditegakkan.
Padahal, dalam proses itu, sering kali si korban belum siap.
Dalam wawancara bersama seorang penyintas kekerasan seksual yang kisahnya viral di TikTok, ia berkata lirih :
“Saya ingin keadilan, tapi saya tidak ingin seluruh hidup saya menjadi bahan konsumsi orang-orang yang bahkan tidak saya kenal.”
Efek trauma tidak selesai saat pelaku dipenjara. Bahkan bisa jadi, trauma paling berat datang setelah proses hukum dimulai.
Korban harus menceritakan ulang kejadian pahit berkali-kali di kantor polisi, di pengadilan, di ruang mediasi, bahkan di hadapan publik lewat wawancara media.
Ketika kasus menjadi viral, ruang privat untuk sembuh menjadi makin sempit. Korban merasa harus kuat demi membalas dukungan publik. Ia merasa tidak boleh menangis, tidak boleh ragu, tidak boleh salah sedikit pun. Karena satu kesalahan, dan kepercayaan publik bisa runtuh.
Sebuah studi dari Lembaga Psikologi Indonesia menyebutkan bahwa penyintas yang kisahnya viral memiliki tingkat stres pascatrauma (PTSD) yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyintas yang melalui jalur hukum secara tertutup.
Ironisnya, publik yang semula bersimpati bisa dengan cepat berubah menjadi penghakim jika narasi tidak sesuai harapan mereka.
Salah satu bahaya terbesar dari keadilan yang viral adalah anggapan bahwa korban adalah milik publik. Setiap keputusan korban dipertanyakan. Setiap langkahnya dinilai. Ada tekanan besar untuk menjadi simbol perjuangan yang sempurna.
Padahal korban adalah manusia. Mereka punya hak untuk sembuh dalam diam. Untuk tidak selalu menjadi bagian dari orasi. Untuk tidak selalu menjadi “bahan konten”.
Apakah kita pernah bertanya, bagaimana perasaan korban saat namanya disebut-sebut setiap hari? Saat wajahnya muncul di televisi, di YouTube, di podcast, bahkan di meme?
Di sinilah restorative justice memberikan cahaya baru. Dalam RJ, privasi dan keamanan korban adalah prioritas. Dialog dilakukan secara tertutup, personal, dan dengan pendampingan.
Tidak ada kamera. Tidak ada live-stream. Hanya ada ruang aman untuk menyampaikan luka, meminta maaf, dan menciptakan penyembuhan.
Ketika kita membagikan kisah korban, apakah kita melakukannya karena ingin membantu atau karena kita ingin menjadi bagian dari cerita viral?
Apakah kita benar-benar mendengarkan korban? Atau kita hanya mendengar apa yang ingin kita dengar?
Keadilan sejati tidak harus viral. Ia harus hadir di ruang-ruang sunyi, di desa-desa yang jauh dari sinyal, di ruang konseling yang tertutup, di meja-meja mediasi yang sederhana.
Karena korban yang benar-benar ingin sembuh, tidak butuh tepuk tangan, tapi butuh pelukan. Tidak butuh trending topic, tapi butuh sistem hukum yang mendengar, memahami, dan melindungi.
Sudah saatnya kita bertanya bukan hanya “apa yang terjadi,” tapi juga “bagaimana kita menyikapinya.” Karena kadang, niat baik pun bisa menyakiti jika dilakukan tanpa hati-hati.
Dan ketika keadilan mampu berjalan tanpa harus menjadi tontonan, maka kita tahu: hukum telah tumbuh. Bukan hanya menjadi alat keadilan, tapi juga menjadi ruang pemulihan yang sesungguhnya.
Di suatu pagi yang cerah, saya duduk bersama seorang ibu di sebuah warung kopi sederhana di pinggiran kota. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia bercerita tentang anaknya yang ditahan karena membela diri dari pencurian. Laporan sudah dibuat, bukti sudah diserahkan, namun aparat tak kunjung bergerak. Hingga akhirnya, video kejadian itu viral di media sosial, barulah keadilan mulai berpihak padanya.
Kisah seperti ini bukanlah hal baru. Banyak warga yang merasa bahwa keadilan hanya datang setelah dunia maya bersuara. Fenomena “No Viral No Justice” menjadi cermin dari sistem hukum kita yang masih memiliki banyak celah.
Untuk mengembalikan kepercayaan publik, langkah-langkah berikut perlu diambil:
• Transparansi dalam Penanganan Perkara: Mahkamah Agung telah memulai langkah ini dengan menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan . Namun, implementasinya perlu diperkuat hingga ke tingkat daerah.
• Respons Cepat terhadap Laporan Masyarakat : Aparat penegak hukum harus memiliki sistem yang memungkinkan mereka merespons laporan dengan cepat dan tepat. Keterlambatan hanya akan menambah ketidakpercayaan publik.
• Penguatan Lembaga Pengawasan Internal: Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam mencegah maladministrasi dan korupsi. Penguatan APIP dapat meningkatkan akuntabilitas dan integritas lembaga penegak hukum .
• Pendidikan Hukum untuk Masyarakat Luas: Masyarakat yang melek hukum akan lebih mampu memperjuangkan hak-haknya dan memahami proses hukum yang berlaku. Program edukasi hukum perlu digalakkan, terutama di daerah-daerah terpencil.
Di era digital, jurnalis dan influencer memiliki kekuatan luar biasa dalam membentuk opini publik. Namun, kekuatan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab moral.
• Verifikasi Informasi: Sebelum membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Informasi yang salah dapat merusak reputasi seseorang dan mengganggu proses hukum.
• Menghindari Sensasionalisme: Fokuslah pada fakta dan data, bukan pada drama yang dapat memicu emosi publik secara berlebihan.
• Menjaga Privasi Korban: Dalam memberitakan kasus hukum, identitas korban harus dilindungi untuk mencegah trauma lanjutan.
• Menjadi Jembatan antara Masyarakat dan Aparat Hukum: Jurnalis dan influencer dapat membantu menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pihak berwenang, bukan menggantikan peran hakim atau jaksa.
Teknologi seharusnya menjadi alat untuk mempermudah proses hukum, bukan menjadi tujuan akhir.
• Aplikasi Pengaduan Digital: Kejaksaan Agung telah meluncurkan e-PROWAS, sebuah layanan pengaduan masyarakat elektronik yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja aparat Kejaksaan . Aplikasi seperti ini perlu disosialisasikan dan diintegrasikan dengan lembaga lain seperti LPSK dan Komnas HAM.
• Sistem Peradilan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI): Sistem ini memungkinkan penanganan perkara secara lebih cepat, akurat, akuntabel, dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum .
• Peningkatan Literasi Digital : Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai penggunaan teknologi dalam proses hukum, agar mereka dapat memanfaatkannya
Mengurai benang kusut dalam penegakan hukum bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, jurnalis, influencer, dan masyarakat. Dengan transparansi, respons cepat, pengawasan yang kuat, edukasi hukum, dan pemanfaatan teknologi yang bijak, kita dapat membangun sistem hukum yang adil dan terpercaya.
Dalam sistem hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi pedoman utama dalam proses penegakan hukum pidana. KUHAP menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum, antara lain asas legalitas, keadilan, dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini seringkali menghadapi tantangan, terutama dengan adanya tekanan dari media sosial dan opini publik.(Legalitas)
Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya. Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Prinsip ini bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa hukum tidak berlaku surut.(lawyer-ahdanramdani com)
Prinsip keadilan dalam hukum acara pidana menekankan perlakuan yang adil dan setara bagi setiap individu di hadapan hukum. Hal ini mencakup hak-hak tersangka dan terdakwa, seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”(Legalitas, Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut, lawyer-ahdanramdani com)
Asas kepastian hukum bertujuan untuk memberikan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan konsisten. Namun, dalam era digital, kepastian hukum seringkali terganggu oleh tekanan dari media sosial dan opini publik yang dapat mempengaruhi proses hukum.
Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan menuntut keadilan. Fenomena “No Viral No Justice” mencerminkan kecenderungan di mana aparat penegak hukum baru bertindak setelah kasus tertentu menjadi viral di media sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan integritas sistem peradilan pidana.(Journal UIi)
Tekanan dari media sosial dapat mempengaruhi proses hukum, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Misalnya, dalam kasus yang mendapat sorotan publik, aparat penegak hukum mungkin merasa terdorong untuk mempercepat proses hukum atau menjatuhkan hukuman yang lebih berat demi memenuhi ekspektasi publik. Sebaliknya, kasus yang tidak mendapat perhatian media sosial mungkin diabaikan atau diproses dengan lambat.
Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum dan dapat merusak prinsip-prinsip dasar dalam hukum acara pidana. Asas praduga tak bersalah, misalnya, dapat terabaikan ketika opini publik sudah menghakimi seseorang sebagai bersalah sebelum proses hukum selesai.
Demikian pula, asas keadilan dan kepastian hukum dapat terganggu oleh tekanan dari media sosial yang menuntut hasil tertentu tanpa mempertimbangkan proses hukum yang adil dan objektif.(lawyer-ahdanramdani.com, Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut)
Untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana di era digital, diperlukan upaya bersama dari semua pihak. Aparat penegak hukum harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar dalam hukum acara pidana dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari media sosial. Masyarakat juga perlu memahami bahwa keadilan tidak dapat dicapai hanya melalui viralitas di media sosial, tetapi melalui proses hukum yang adil dan transparan. (Journal UIi)
Pendidikan hukum bagi masyarakat luas menjadi penting agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum. Selain itu, media dan influencer memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, serta tidak menghakimi seseorang sebelum proses hukum selesai.
Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum acara pidana dapat tetap dijunjung tinggi dan sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara adil dan efektif, meskipun di tengah tantangan era digital.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi merupakan fondasi utama yang menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Salah satu pasal yang menegaskan hal ini adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:(Sumber kumparan)
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Pasal ini menegaskan bahwa keadilan bukanlah sebuah privilese yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang, melainkan hak asasi yang melekat pada setiap individu. Namun, dalam praktiknya, realitas di lapangan sering kali menunjukkan ketimpangan yang mencederai semangat konstitusi.
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena yang dikenal dengan istilah “No Viral No Justice”. Istilah ini mencerminkan situasi di mana penegakan hukum baru berjalan efektif setelah kasus tertentu menjadi viral di media sosial. Artinya, tanpa sorotan publik yang masif, aparat penegak hukum cenderung lambat atau bahkan abai dalam menangani kasus-kasus tertentu.
Fenomena ini menjadi kritik tajam terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, fenomena “No Viral No Justice” mencerminkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik. Banyak kasus yang baru mendapatkan perhatian setelah viral di media sosial, menunjukkan bahwa sistem hukum kita masih reaktif terhadap tekanan publik. (Sumber KOMPAS com)
Ketika keadilan bergantung pada viralitas, maka prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi terancam. Mereka yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk membuat kasusnya viral berisiko diabaikan, meskipun memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Ini menunjukkan perlunya reformasi sistem hukum agar dapat menjamin keadilan bagi semua, tanpa terkecuali.
Sebagai contoh, kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat atau kelompok marginal sering kali tidak mendapatkan perhatian yang layak karena kurangnya akses terhadap media sosial atau jaringan yang dapat membantu memviralkan kasus mereka. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan, yang bertentangan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi sistem hukum yang menyeluruh. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
1. Penguatan Lembaga Penegak Hukum :
1. Meningkatkan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum agar dapat bekerja secara profesional dan independen, tanpa terpengaruh oleh tekanan publik atau viralitas kasus.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong transparansi dalam proses penegakan hukum, sehingga masyarakat dapat memantau dan menilai kinerja aparat penegak hukum secara objektif.
3. Peningkatan Akses terhadap Keadilan: Memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat, terutama kelompok marginal, untuk mendapatkan bantuan hukum dan informasi mengenai hak-hak mereka.
4. Edukasi Hukum bagi Masyarakat : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi, sehingga mereka dapat memahami dan memperjuangkan hak-haknya secara tepat.
Bayangkan sebuah dunia di mana keadilan tidak lagi bergantung pada seberapa banyak “like” atau “share” yang diterima sebuah unggahan di media sosial. Sebuah dunia di mana setiap individu, tanpa memandang status sosial atau akses terhadap teknologi, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa kita masih jauh dari dunia ideal tersebut.
Fenomena “No Viral No Justice” telah menjadi cermin yang memantulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal. Ketika kasus-kasus hanya mendapatkan perhatian setelah menjadi viral, kita harus bertanya : Apakah sistem hukum kita benar-benar bekerja untuk semua, atau hanya untuk mereka yang mampu menarik perhatian publik?
Kita tidak ingin hidup dalam dunia di mana keadilan hanya diberikan kepada mereka yang viral. Kita ingin dunia di mana keadilan adalah hak semua orang, bukan hak yang harus diperjuangkan lewat trending topic.
Fenomena “No Viral No Justice” seharusnya menjadi alarm keras bahwa sistem kita belum sempurna. Ia bukan hanya sebuah kritik, tapi juga peluang untuk memperbaiki. Kita bisa dan harus menciptakan sistem hukum yang bekerja bukan karena sorotan, tapi karena nurani, profesionalisme, dan integritas.
Dan untuk itu, kita semua punya peran. Aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan adil dan tanpa pandang bulu. Media dan influencer harus menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Masyarakat harus aktif dalam mengawasi dan menuntut keadilan, bukan hanya melalui media sosial, tetapi juga melalui saluran hukum yang tersedia.
Dengan kerja sama semua pihak, kita dapat membangun sistem hukum yang adil dan terpercaya, di mana keadilan tidak lagi bergantung pada viralitas, tetapi menjadi hak yang dijamin dan ditegakkan untuk setiap warga negara.